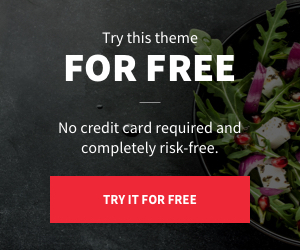Snouck Hurgronje menyarankan pemerintah kolonial untuk menghancurkan upaya umat Islam di ranah politik.
Christiaan Snouck Hurgronje membawa kebaruan bagi metode Belanda dalam menaklukkan Nusantara. Menurut Jajat Burhanudin dalam Ulama dan Kekuasaan (2012), orientalis berhaluan liberal itu adalah sarjana pertama yang mengkritik kebijakan kolonial tentang haji. Baginya, gelar haji dan pakaian Arab tak sepatutnya diatur tegas. Begitu pula dengan pembatasan haji.
“Maka saya berani menganjurkan dengan sungguh-sungguh agar mereka yang mau naik haji, jika tidak ada keberatan khusus lainnya yang menghalangi niatnya, hendaknya diberi paspor yang mereka minta,” demikian guru besar Universitas Leiden tersebut.
Dalam karyanya, Mekka, ia menuliskan pengamatannya terhadap komunitas Jawi (Nusantara) di Tanah Suci. Ia berpendapat, jamaah haji, pelajar, dan pengikut tarekat asal Nusantra selama berada di Makkah tak menunjukkan tanda-tanda “fanatisme.” Mereka hanya mewakili suatu jaringan intelektual antara Nusantara dan jantung dunia Islam.
Berbeda halnya dengan kalangan yang disebutnya “kaum fanatik.” Menurut Christiaan, mereka dipengaruhi ideologi jihad. Baginya, inilah akar bahaya. Sebab, ideologi tersebut membuat masyarakat Pribumi menentang pemerintah kolonial. Pengamatan langsung atas Perang Aceh semakin menguatkan pandangannya itu.
Cegah Islam Politik
Sebagai ilmuwan yang dididik dalam lingkungan kampus liberal, Christiaan menganggap peradaban Barat sekular sebagai puncak evolusi kebudayaan umat manusia. Alhasil, segala peradaban lain, termasuk Islam, harus tunduk. Ideologi jihad, lanjut dia, adalah kendala yang mesti dilenyapkan.
Bahasa yang dipakainya dalam melawan jihad bukan “penjajahan”, melainkan “pemberadaban.” Yakni, melalui pendidikan yang menjadikan anak-anak Pribumi berkiblat pemikiran dan tindakan kepada Barat. Pemberlakuan Politik Etis (Ethische Politiek) di Hindia Belanda sejak 1900-an memuluskan realisasi visi Christiaan.
Selain itu, sang orientalis juga menyarankan pemerintah kolonial agar membuat berbagai kebijakan yang memisahkan umat Islam dari dunia politik. Janganlah rezim penguasa mengganggu penduduk yang menjalankan sebatas ritual-ritual agama. Namun, begitu umat agama ini (Islam) menyentuh soal-soal politik, maka pemerintah harus segera menghancur-leburkannya.
Janganlah rezim penguasa mengganggu penduduk yang menjalankan sebatas ritual-ritual agama. Namun, begitu umat agama ini (Islam) menyentuh soal-soal politik, maka pemerintah harus segera menghancur-leburkannya.
Menurut Snouck Hurgronje, sejatinya masyarakat Nusantara lebih patuh pada hukum adat ketimbang hukum agama (syariat). Dalam hal ini, ia mengamini teori resepsi, yakni suatu penduduk akan menerima (meresepsi) suatu aturan bila memang sesuai dengan adat istiadat setempat.
Melalui berbagai suratnya, ia mendesak agar pemerintah menghargai wibawa hukum adat di samping hukum yang dibawa dari Eropa ke negeri jajahan. Dengan rezim mengangkat hukum adat, secara implisit ia bermaksud, umat Islam di Nusantara dapat terbujuk untuk meninggalkan syariat.
Pasca-Hurgronje
Kini, sudah lewat banyak dekade sejak Snouck Hurgronje meninggal. Bahkan, masa penjajahan Belanda pun sudah pergi dari Bumi Pertiwi. Akan tetapi, terminologi “Islam Politik” yang dideteksi orientalis tersebut masih terasa adanya sampai saat ini.
Wacana memisahkan Islam dari kehidupan politik masih saja terasa. Jargon-jargon semisal “hapuskan peraturan daerah (perda) syariat” atau “jangan politisasi masjid”—untuk menyebut beberapa contoh saja—sesungguhnya juga terpengaruh sekulerisme ala Hurgronje.
“Pemerintah jajahan Belanda tempo dulu juga sudah melarang politisasi masjid. Dengan mengikuti arah Snouck Hurgronje, pemerintah Belanda mengizinkan eksistensi masjid dan kaum Muslim itu hanya untuk soal ritual dan ibadah,” mengutip guru besar Universitas Paramadina, Prof Abdul Hadi WM (Republika, 20/9/2018).
Ada kesan bahwa soal Islam politik terus dan masih saja dicurigai bahkan sesudah RI merdeka.
Ada kesan bahwa soal Islam politik terus dan masih saja dicurigai bahkan sesudah RI merdeka. Pada puncak masa kekuasaan presiden Sukarno, situasi perpolitikan nasional sempat memanas dengan manuver-manuver Partai Komunis Indonesia (PKI). Muncullah jargon-jargon “nyinyir” kepada gerakan Islam yang memperjuangkan ide politik (baca: Islam Politik).
Di akar rumput, para simpatisan komunis memunculkan seruan: waspadalah kepada kaum sarungan! Slogan serupa pun banyak bermunculan saat era 1960-an. Salah satu contohnya adalah menyamakan para pemimpin pesantren yang punya lahan dan sawah luas sebagai “setan desa.” Lebih tak habis pikir lagi, amil zakat pun dianggap sebagai bagian dari “setan desa” tersebut (lihat Kamus Gestok, hlm. 263).
Jatuhnya rezim Bung Karno sesudah peristiwa G30S diiringi timbulnya Orde Baru. Memasuki 1980-an, kembali perpolitikan nasional dibuat panas dengan isu “kanan ekstrem.” Ada kecurigaan-kecurigaan yang, implisit maupun eksplisit, menyasar Islam Politik. Itu terbaca ketika terjadi perdebatan panas soal rancangan undang-undang (RUU) peradilan agama.
Padahal, sejarah mencatat bahwa tokoh Muslim, Mohammad Natsir, layak disebut sebagai Bapak NKRI.
Muncul tuduhan bahwa para pendukungnya hendak mengembalikan “tujuh kata” yang hilang dari Piagam Jakarta atau ingin menjadikan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) “negara agama”.
Padahal, sejarah mencatat bahwa tokoh Muslim, Mohammad Natsir, layak disebut sebagai Bapak NKRI. Sebab, berkat Mosi Integral yang diajukannya pada 3 April 1950, RI melepaskan bentuk federal sehingga memilih negara kesatuan.
Sumber: Republika