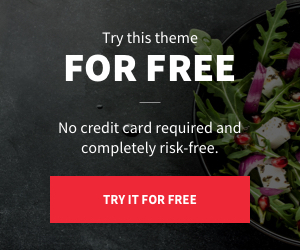Rasa ketidakadilan yang meluas di kalangan publik berpotensi mendorong rasa tidak percaya kepada aparat negara.
Pada 23 November 1984 harian Kompas memuat tulisan saya berjudul ”Momongan dan Modernisasi Politik: Dilema Kultur Politik Indonesia”. Isinya, kontradiksi dua arus kebijakan pimpinan negara antara usaha mempertahankan politik tradisional dan modernitas.
Sementara ”momongan” (sebuah konsep tradisional Jawa) diterapkan sebagai manajemen politik untuk menjaga stabilitas, pada saat negara Orde Baru melancarkan pembangunan ekonomi dengan premis modernisasi.
Kini, di ujung 2023, saya melihat justru manajemen politik ”momongan” itu kian memudar. Konsep yang—mengutip karya klasik Soemarsaid Moertono, State and Statecraft in Old Java: A Study of the Later Mataram Period, 16th to 19th Century (1981)—berasal dari kata momong ini mengutarakan bahwa ”momongan” adalah menjaga dengan sayang dan membimbing. Dengan arti dasar ini, agensi pelaku ”momongan”, dengan demikian, harus bisa bertindak sebagai suri teladan (examplary model) dalam bersikap dan bertingkah laku.
Untuk sebagian, sumber pemudaran laku ”momongan” ini karena hilangnya disiplin budaya mematutkan diri kalangan elite. Selama dua tahun belakangan ini, misalnya, rakyat Indonesia menyaksikan khidmatnya upacara peringatan kemerdekaan bercampur baur dengan aksi joget para petinggi negara.
Selama dua tahun belakangan ini, misalnya, rakyat Indonesia menyaksikan khidmatnya upacara peringatan kemerdekaan bercampur baur dengan aksi joget para petinggi negara.
Sebagian lainnya adalah karena struktur kekuasaan politik reformasi 1998 yang terpencar-pencar. Sementara benar kenyataan ini merefleksikan semangat demokrasi, absennya the examplary model kalangan pemimpin telah membuat keterpencaran kekuasaan tersebut kehilangan tujuan mulia, bahkan untuk membangun diri dan organisasi sendiri.
Bagaimana memahami sebuah partai besar melaksanakan rapat pimpinan (rapim) hanya untuk mengesahkan seorang liyan menjadi calon pemimpin nasional, sementara para kader yang telah berpeluh tercecer di belakang? Adilkah tindakan ini bagi para kader. Sebab, bahkan sang liyan yang dapat keistimewaan itu tak perlu menyatakan diri bagian integral partai tersebut? Di sini, walau tak diungkapkan ke publik, faktor rasa keadilan mengemuka.
”Glebagan”, ”gogol ngarep”, dan ”gogol mburi”
Kritik terhadap konsep dan sistem kekuasaan Jawa telah lama dilakukan. Di antaranya adalah buku yang saya tulis berjudul Refleksi Paham Kekuasaan Jawa dalam Indonesia Modern (1986).
Akan tetapi, betapa pun represifnya sistem kekuasaan tradisional itu, kita masih menemukan konsep, dan di atas itu, praktik laku adil justru ditujukan kepada kalangan petani, lapisan terbawah dalam struktur kekuasaan Jawa tradisional.
Dalam studinya tentang sistem pajak dan distribusi kekayaan di zaman Mataram abad ke-16-19, Soemarsaid Moertono menemukan kata glebagan. Moertono, dalam karyanya State and Statecraft di atas, mengartikan glebagan tersebut sebagai turnover. Kita bisa mengartikan kata bahasa Inggris ini sebagai pergantian atau penggiliran.
Dalam tafsir saya, glebagan ini adalah konsep justice wealth distribution di kalangan petani Jawa masa lalu. Ini terutama jika konsep itu dikaitkan dengan kata gogol ngarep dan gogol mburi. Di dalam sistem kepemilikan komunal, para petani Jawa di masa lalu bukanlah pemilik tanah, karena seluruh kekayaan, terutama tanah, adalah milik raja.
Maka, status mereka atas tanah adalah penggarap. Rajalah yang berhak mendistribusikan penggarapan tanah ke petani. Kendati demikian, telah ada sistem caton (penjatahan) dalam kepemilikan komunal itu. Distribusi penggarapan ini dipraktikkan dengan adil. Laku ini terlihat pada pelaksanaan sistem glebagan terhadap dua jenis penggarap tanah: gogol ngarep dan gogol mburi.
Secara harfiah, gogol ngarep adalah penggarap (tanah) yang berada di arep (depan) yang secara konseptual berarti berada di wilayah irigasi. Sementara gogol mburi adalah penggarap yang mendapat caton (jatah) di mburi atau di belakang. Ini berarti bahwa penggarap tersebut mendapatkan caton jauh dari wilayah irigasi. Ini berarti bahwa tiap-tiap caton tersebut berbeda dalam hal produktivitas tanah.
Karena itu, untuk mempraktikkan keadilan secara konkret, penguasa Jawa, seperti diungkapkan Moertono, mendistribusikan besaran caton tanah garapan gogol ngarep dan gogol buri tidak sama. Caton bagi gogol buri pada umumnya lebih luas dari gogol ngarep.
Akan tetapi, sistem caton tanah yang tampak telah proporsional itu masih dianggap belum cukup adil. Sebab, karena dekat dengan kawasan irigasi, gogol ngarep akan lebih diuntungkan secara permanen dibandingkan dengan gogol mburi. Oleh karena itulah, pengenaan sistem glebagan dianggap sebagai tindakan pamungkas, yaitu penggiliran tahunan para gogol (penggarap). Gogol tahun sebelumnya berada di arep (dekat wilayah irigasi) dipindahkan ke buri (jauh dari wilayah irigasi) dan sebaliknya.
Walau debatable, saya ingin mengatakan bahwa praktik glebagan yang mencerminkan keadilan dalam kekuasaan Jawa tradisional ini menjelaskan mengapa tak terjadi pemberontakan petani yang signifikan dengan motif material.
Walau debatable, saya ingin mengatakan bahwa praktik glebagan yang mencerminkan keadilan dalam kekuasaan Jawa tradisional ini menjelaskan mengapa tak terjadi pemberontakan petani yang signifikan dengan motif material. Sebagai perbandingan, kita menemukan fakta dalam sejarah Perancis, di mana, apa yang disebut Barrington Moore Jr sebagai small property owners, untuk sementara, luput menjadi partisipan Revolusi Perancis (1789-1799).
Mereka ini, cetus Moore dalam buku terkenalnya, Social Origins of Dictatorship and Democracy: Lord and Peasant in the Making of Modern World (1974), adalah para petani yang selama dua abad sebelum revolusi itu telah mengalami pemiskinan. Kurang minat mereka berpartisipasi ke dalam revolusi yang mengubah dunia itu adalah karena para petani kaya membiarkan mereka menggembala di tanah-tanah luas milik para tuan tanah tersebut.
Menghindari kehadiran kembali ”stranger king”
Dalam usaha mencari penjelasan mengapa proses kolonialisasi Barat berlangsung ”mulus” di kawasan Nusantara, David Henley menciptakan frasa menarik: stranger king (raja [yang berasal dari negeri] asing). Ini diungkapkan dalam tulisannya, ”Conflict, Justice, and the Stranger-King: Indigenous Roots of Colonial Rule in Indonesia and Elsewhere” (Modern Asian Studies 38, 2004). ”Kemulusan” proses kolonialisasi Barat ini terlihat di anak judul artikel Henley: indigenous roots of colonial rule (akar-akar pribumi pemerintahan kolonial).
Dengan memanfaatkan hasil studi sejarah dan antropologi yang cukup kaya, Henley menyatakan bahwa problem terbesar kelompok-kelompok masyarakat Nusantara adalah konflik yang konstan di antara sesama mereka. Konflik yang berlangsung secara konstan di antara kelompok masyarakat atau etnik ini menyebabkan absennya wasit yang dianggap otoritatif dan adil dari kalangan yang terlibat konflik itu, yaitu apa yang disebut Henley sebagai combinations of third-party mediation, impartial adjudication, and legal enforcement.
Sebagai akibatnya, lanjut Henley, para pemimpin pribumi tak memiliki seperangkat genius (kecerdasan) untuk mengelola konflik. Sebaliknya, mereka punya prasangka ala Hobbes tentang ketidakterelakkan konflik dalam kehidupan berpola aneka suku itu dan karena itu berhasrat tinggi akan adanya intervensi negara guna mengatasi masalah ini.
Di sini, berdasarkan data studi sejarah dan antropologi Sulawesi Tengah dan Utara, Henley menyatakan bahwa kehadiran kalangan asing sebagai juru penengah bukan saja menjadi sesuatu yang sangat eksistensial dalam menciptakan kestabilan dan kedamaian di tengah masyarakat pribumi. Sang juru damai itu benar-benar berasal dari kalangan asing yang tak punya ikatan darah (lack of blood ties) dengan mereka.
Ini semua untuk memberikan guarantee (jaminan) dan impartiality (ketidakberpihakan) wasit yang berasal dari asing itu. Di sini, Henley mengungkap fakta sejarah bahwa sepanjang abad ke-17, ke-18, dan ke- 19, VOC (dibangun di Belanda pada 1602) dan pemerintah kolonial Belanda yang mewarisinya menerima undangan yang tak diminta untuk membangun benteng-benteng di Sulawesi Utara. Ini ”terpaksa” dipenuhi VOC walau Sulut pada masa itu secara ekonomi tak terlalu menguntungkan.
Inilah yang menjelaskan mengapa segelintir orang asing yang berhimpun di dalam VOC mampu mengontrol penduduk Sulut sebanyak 200.000 jiwa dan bersedia membayar pajak kepada mereka. Dan, pada 1910, ketika seluruh Sulawesi Tengah telah berada di bawah kekuasaannya, pemerintah kolonial di Manado bisa menguasai dan memajaki penduduk hampir 1 juta jiwa yang luas wilayahnya setara Spanyol.
Hasrat akan keadilan kalangan pribumi yang saling berperang inilah yang menjadi akar sosial bagi lahirnya proses kolonialisasi Nusantara yang, sebagaimana telah dinyatakan, berjalan ”mulus”.
Di sini, mengutip studi antropologis Meike Schunten pada 1998, Henley menegaskan bahwa Belanda tak perlu melakukan kebijakan adu domba (divide and rule). Sebab, lanjutnya, the division existed before their arrival (perpecahan telah ada sebelum kedatangan mereka).
Inilah, antara lain, yang menjadi latar belakang lahirnya stranger king dari Henley. Seorang raja asal asing yang dianggap mampu bertindak adil oleh semua kelompok masyarakat atau etnik pribumi yang bertarung secara kontinu.
Buat kalangan pribumi Sulawesi Utara pada masa itu, yang penting buat mereka bukanlah kekuatan militer atau ekonomi, melainkan judicial, sistem kehakiman yang adil. Karena itu, tambah Henley, para pemimpin politik yang efektif adalah polisi dan hakim.
Kestabilan masyarakat, dengan demikian, bertumpu pada the more impartial arbitration of a more complete outsider. Dan, yang lebih disukai untuk menjadi hakim tersebut itu kalangan yang cukup kaya. Mengapa? Sebab, mereka kebal dari sogokan dan cukup kuat secara militer untuk tak berpihak kepada salah satu yang berperang.
Hasrat akan keadilan kalangan pribumi yang saling berperang inilah yang menjadi akar sosial bagi lahirnya proses kolonialisasi Nusantara yang, sebagaimana telah dinyatakan, berjalan ”mulus”. Bukankah pemapanan kekuasaan kolonial di Jawa terjadi ketika penguasa Mataram terpaksa mengundang stranger king ini di dalam Perang Trunojoyo yang meletus pada 1776?
Secara teoretis, kemunculan stranger king ini bisa dilihat sebagai refleksi modern colonial state formation (pembentukan negara kolonial modern). Akan tetapi, di dalam konteks politik nasional dewasa ini, kita bisa becermin pada fakta sejarah ini. Bahwa rasa ketidakadilan yang meluas di kalangan publik berpotensi mendorong rasa tak percaya kepada aparat negara. Dan rasa ketakpercayaan ini harus kita hindarkan.
Sebab, ini berpotensi menghadirkan stranger king baru, yaitu seperti terjadi pada masa Orde Baru (1967-1998), kalangan yang mengontrol persenjataan. Seperti di mana pun, kita tak bisa menitip perkembangan demokrasi yang masih bayi ini pada kalangan terakhir itu.
Sumber : Kompas.id