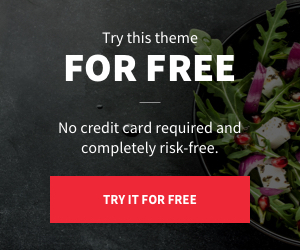Jakarta – Jajak pendapat Litbang Kompas, 19 – 21 Juni 2023 membenarkan kekhawatiran publik menyangkut potensi polarisasi politik menjelang dan saat Pemilu 2024. Responden yang khawatir menembus 56 persen. Ini tak jauh berbeda dengan hasil jajak pendapat serupa, 23 – 24 Agustus 2018 (jelang Pemilu 2019), di mana 57,6 persen responden mengakui terjadi polarisasi di masyarakat.
Saban menjelang pemilu, terutama sejak 2004, polarisasi politik dan lalu menjurus ke polarisasi sosial menjadi bahaya laten di negeri kita. Apakah ini murni wujud dari persaingan politik yang keras dan panas? Atau, adakah ini merupakan kontribusi dari regulasi atau suprastruktur politik yang ikut memicunya secara langsung dan tidak langsung?
Pemilu transisi pertama dari otoritarianisme ke demokrasi telah berlangsung pada 1999 silam. Di sini pesta demokrasi berubah lantaran seluruh warga negara punya ruang yang sama dan terbuka untuk mendirikan partai politik. PDIP ketika itu menang pemilu dengan raihan suara menembus lebih dari 33 persen. Itu rekor partai yang dipiloti Megawati Soekarnoputri ini dan belum sanggup disamai atau dipecahkan oleh PDIP sendiri dan partai lain yang berlaga di pemilu sejak 1999.
Bahkan Partai Demokrat yang melesat jadi nomor satu di Pemilu 2009 cuma menghimpun 20,85%. Bedanya PDIP di Pemilu 1999 gagal mengantarkan Megawati jadi presiden. Sedangkan Demokrat pada 2009 sukses membawa Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) jadi presiden untuk periode kedua. Begitulah, pada 1999 pemilihan presiden dan wakil presiden masih dilaksanakan oleh MPR. Megawati menjadi “korban” dari polarisasi politik yang berembus saat itu ketika kekuatan nasionalis dan Islam berebut kendali untuk memimpin negeri yang baru lepas dari rezim otoriter Soeharto.
Megawati merepresentasikan kubu nasionalis, sedangkan BJ Habibie yang presiden incumbent dan meracik ICMI 1990 serta punya bendera Golkar mewakili Islam. Ketakutan atas potensi benturan dua “gajah” itu dalam politik Indonesia mengilhami Amien Rais membentuk Poros Tengah. Ini sebuah poros politik yang mencari jalan tengah atas sikut-sikutan antara kubu nasionalis dan Islam. Dan, Amien dkk sukses mengantar sosok Abdurrahman Wahid (Gus Dur) sebagai capres dalam pemilihan lewat MPR.
Ditambah faktor ditolaknya pertanggungjawaban Habibie oleh MPR, praktis peluang Habibie maju dalam Pilpres 1999 sirna. Alhasil bukan Habibie yang bertarung dengan Megawati, melainkan Gus Dur. Dialah sosok yang di dalam dirinya tertanam kuat citra Islam dan nasionalis. Itulah jalan tengah dari Poros Tengah yang digagas Amien Rais.
Ketika akhirnya Megawati kalah kontra Gus Dur dalam pemilihan di MPR, polarisasi politik dan sosial dapat dicegah karena Gus Dur yang punya hubungan dekat dengan Megawati dan PDIP mau merangkulnya dalam pemerintahan. Partai yang didirikan Gus Dur, yaitu PKB membuka jalan kepada Megawati untuk maju dalam pemilihan wapres dan akhirnya menang. Duet Gus Dur-Megawati pun memimpin Indonesia dengan kesadaran kuat untuk secara luas melakukan akomodasi politik terhadap partai-partai.
Gus Dur menamai kabinetnya sebagai Kabinet Persatuan Nasional. Itulah rekayasa politik yang sukses mencairkan polarisasi di pemilu masa transisi. Sebuah eksemplar yang menandai dan menegaskan bahwa politik Indonesia itu beragam, majemuk. Cara menanggapinya pun perlu kelenturan, kadang tak umum, tapi solutif.
Tetap Membayangi
Setelah demokrasi langsung diadaptasi negeri ini, polarisasi politik tetap membayangi. Yang paling menonjol adalah Pilpres 2014 dan 2019. Dalam dua kali pemilu itu, Joko Widodo dan Prabowo Subianto bertarung memperebutkan kursi presiden. Kali ini dua kandidat tak mewakili kekuatan nasionalis dan Islam secara kaku. Secara kasat mata dua sosok ini dapat dikatakan mewakili kubu nasionalis.
Tapi, di era internet dan media sosial, polarisasinya makin menjadi-jadi, keras, dan bertahan lama–bahkan setelah pilpresnya kelar dan sang pemenang dilantik jadi presiden.Dalam kasus 2014, terlihat kontestasi antara Jokowi dan Prabowo terjadi antara lain karena partai-partai yang memiliki kekuatan elektoral (kursi dan suara secara nasional) membiarkan keduanya melenggang tanpa kontestan ketiga.
Partai Demokrat sempat menggelar konvensi capres dengan pemenang Dahlan Iskan. Golkar pun sempat menimang-nimang Aburizal Bakrie untuk menjadi capres. Tapi, di ujung proses, kedua partai urung memajukan kandidatnya ke panggung Pilpres 2014. Padahal Demokrat dan Golkar bisa saja membuat poros atau koalisi politik dengan pengalaman serta kekuatan elektoral mereka. Tapi ternyata tidak.
Adapun partai lainnya terbelenggu presidential threshold, yaitu ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden yang telah dinaikkan sejak Pemilu 2009. Inilah ketentuan yang membelenggu, karena cuma partai atau gabungan partai dengan sekurang-kurangnya memiliki 20 persen kursi DPR atau 25 persen suara sah nasional yang boleh mencalonkan presiden dan wakil presiden.
Pada 2019 sama saja. Jokowi sebagai lncumbent terlalu kuat. Lagi-lagi cuma Prabowo yang tampil sebagai pesaing. Mengapa ini terjadi? Di samping situasi politik saat itu, secara intrinsik aturan presidential threshold pula yang membelenggu.
Kontras dengan Pilpres 2004, ketika ambang batas atau kuota pencapresan lebih kecil, yaitu 15 persen kursi DPR atau 20 persen suara sah nasional. Waktu itu ada lima pasangan capres/cawapres yang berlaga. Incumbent Megawati berduet dengan Hasyim Muzadi, lalu ada Hamzah Haz-Agum Gumelar, Amien Rais-Siswono Yudohusodo, SBY-Jusuf Kalla, serta Wiranto-Salahuddin Wahid.
Pada Pilpres 2009 pun, masih ada tiga pasangan yang bertarung: Megawati-Prabowo, SBY-Boediono serta Jusuf Kalla-Wiranto. Ketika itu sang incumbent, SBY menang dalam satu putaran. Secara empiris–dan bukan hipotesis lagi–harus dibilang bahwa presidential threshold bertanggung jawab atas minimnya pasangan calon presiden/wapres yang bertarung. Makin besar ambang batas yang diberlakukan, kian sedikit kontestan pilpres. Itu faktor pertama.
Kedua, ditentukan oleh keberanian atau nyali dari partai politik serta kandidat capres/cawapres. Di luar “siap menang dan kalah”, pada Pilpres 2009, Jusuf Kalla maju ke panggung Pilpres juga karena keteguhan untuk menjaga martabat partai. Kengototan seperti ini, dalam perspektif yang lebih holistik, membawa manfaat pada rakyat: para voter yang masuk bilik suara punya lebih banyak alternatif untuk memilih siapa presiden dan wakil presiden yang dianggap layak untuk memimpin Indonesia.
Pelajaran dari Jusuf kalla pada 2009 yang urung diteruskan SBY/Demokrat (2014 dan 2019) serta Golkar (2014 dan 2019) adalah ketika pasangan capres/cawapres berjumlah lebih dari dua, polarisasi politik lebih susut. Kalau pun ada polarisasi, itu tidak lebih keras dan tidak lebih mengkhawatirkan ketimbang Pilpres 2014 serta Pilpres 2019 (ketika pemilihan eksekutif legislatif telah digabungkan dalam satu waktu). Kita berharap Nasdem, Demokrat serta PKS mengikuti jalan Jusuf Kalla 2009.
Harus Ditinjau Ulang
Di atas kertas, keberadaan presidential threshold punya tiga fungsi: memperkuat sistem presidensial, demi efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, serta menyederhanakan sistem multipartai melalui seleksi alam. Kalau berkaca dari pemerintahan SBY (2004-2009) serta Jokowi (2014-2024), tujuan penerapan ambang batas pencapresan itu dapat dikatakan gagal.
Selepas Pemilu 2004, SBY harus merangkul Golkar yang ketika itu berganti nakhoda dari Akbar Tanjung ke Jusuf Kalla. Keberadaan Jusuf Kalla sebagai wapres terlalu mempesona Golkar, yang awalnya bergabung dalam kekuatan oposisi menjadi masuk kabinet (pemerintahan). Dalam pada itu, institusionalisasi kekuatan oposisi untuk menjalankan fungsi check and balance gagal diteruskan Akbar yang kehilangan kendali atas Golkar.
Republik, Presiden, dan Presidensialisme adalah bangunan yang kita hidupi. Tapi presidensialisme di Tanah Air sesungguhnya presidensialisme seolah-olah. Presiden terpilih tak pernah benar-benar dapat membentuk pemerintahan tanpa mempertimbangkan konfigurasi politik di DPR (parlemen). Itulah presidensialisme rasa parlementarisme.
Di masa Gus Dur itu dapat diterima, sebab itulah transisi yang sesungguhnya dari zaman otoritarianisme ke masa demokrasi. Tapi, faktanya “keterusan” sampai sekarang. Di periode kedua pemerintahannya, Jokowi terjebak membentuk koalisi pemerintahan yang jumbo bin tambun. Jokowi bahkan mengawinkan “hal yang tidak umum”: Menyerap kekuatan oposisi, yakni Prabowo dan Sandiaga Uno (Gerindra) ke Kabinet Indonesia Maju.
Di bawah Jokowi, presidensialisme yang dianut Indonesia cuma menyisakan PKS dan Demokrat sebagai oposisi sehingga tak pernah sanggup mengimbangi partai-partai pemilik kursi DPR yang terafiliasi dengan koalisi pemerintah.
Presidential threshold yang berlaku sekarang juga tak membantu penyederhanaan partai politik. Tugas ini sudah ditunaikan aturan lain, yakni parliamentary threshold–ambang batas partai politik yang dapat masuk DPR. Tapi pun harus dikatakan tidak ampuh, atau manjur-manjur amat. Sebab penerapannya tidak progresif, kenaikan ambang batasnya cuma “seunyil” –dari 2,5 persen lalu 3,5 persen dan kemudian 4,0 persen.
Bandingkan dengan presidential threshold yang di awal sudah dipatok 15 persen kursi DPR, dan kemudian 20 persen kursi DPR atau 25 persen suara sah nasional. Komparasi ini jelas-jelas jomplang, atau tidak koheren?
Dengan seluruh penjelasan tadi, jelas dan terang presidential threshold harus ditinjau ulang. Soal ini tak bisa lagi diserahkan kepada Mahkamah Konstitusi yang sudah belasan kali menolak uji materi pasal presidential threshold. Justru DPR, dan juga pemerintah, sebagai aktor aktif pembuat undang-undang yang harus didorong melakukan perubahan yang mendasar.
Konstitusi, UUD 1945 dan hasil amandemennya, tidak mengatur kuota atau ambang batas itu. Sebaliknya perintah konstitusi cuma menegaskan bahwa pencalonan presiden dan wakil presiden hanya melalui partai atau gabungan partai politik.
Kalau tidak sanggup dan emoh menghapus sama sekali, presidential threshold harus dilonggarkan hingga di bawah 10 persen. Dengan cara itu, siapa pun yang bermimpi memimpin Indonesia punya peluang lebih besar maju pilpres. Tugas penting lainnya: mengurangi potensi polarisasi politik yang terus mengancam persatuan bangsa setiap kali digelar pesta elektoral.
Sumber : detikNews